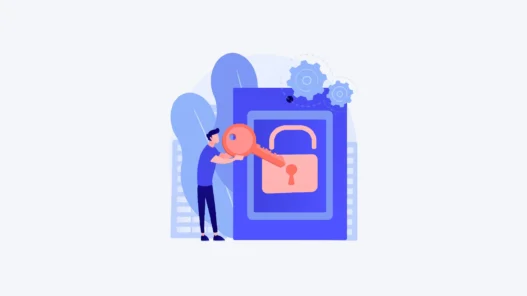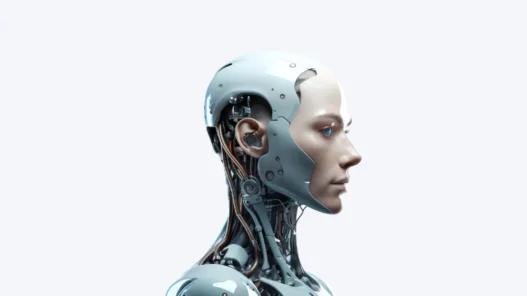Beberapa tahun terakhir, kerap kita temui perusahaan teknologi berlomba-lomba menampilkan citra ramah lingkungan. Mulai dari kampanye pengurangan jejak karbon, hingga slogan seperti komputasi berkelanjutan, narasi tersebut kini menjadi bagian dari strategi pemasaran. Meskipun demikian, di balik warna hijau yang ditonjolkan, tersirat kenyataan yang tidak selalu seindah klaimnya.
Teknologi memang tampak sebagai solusi bagi banyak persoalan ekologis. Kerja jarak jauh, misalnya, diklaim mampu menekan emisi dari transportasi harian. Layanan komputasi awan disebut lebih efisien dibanding server konvensional. Namun, bila menelusuri rantai energi serta konsumsi sumber daya yang menopang semua itu, kita menemukan paradoks. Semakin digital gaya hidup manusia, semakin besar pula jejak lingkungan yang kita tinggalkan.
Lantas, kenapa kita hampir tidak pernah benar-benar tahu seberapa banyak jejak lingkungan yang kita tinggalkan saat menggunakan produk teknologi dalam kehidupan sehari-hari? Di sinilah istilah greenwashing muncul.
Mengenal istilah greenwashing
Greenwashing ialah istilah untuk menggambarkan praktik menutupi dampak lingkungan dengan klaim yang palsu dan berlebihan, kini telah menjadi isu serius di industri teknologi.
Greenwashing dipadankan dengan istilah pencucian hijau dalam bahasa Indonesia. Greenwashing bukanlah fenomena baru. Istilah tersebut muncul pada era 1980-an, ketika beberapa perusahaan besar mulai menggunakan retorika peduli lingkungan tanpa mengubah praktik dasarnya.
Dalam konteks teknologi, bentuknya jauh lebih halus. Greenwashing sering hadir dalam bentuk kampanye keberlanjutan yang dikemas dengan desain visual modern, laporan tahunan dengan angka efisiensi energi, atau komitmen emisi karbon nol bersih yang masih penuh catatan kecil di bawahnya.
Salah satu contoh yang patut disoroti adalah klaim bahwa komputasi awan dapat membantu perusahaan menghemat energi. Secara teori, memang benar. Dengan menggabungkan banyak server dalam satu pusat data, efisiensi energi dapat ditingkatkan, dibandingkan ketika setiap perusahaan memiliki server sendiri. Namun dalam praktiknya, skala konsumsi energi pusat data global kini telah mencapai titik yang mengkhawatirkan.
Berdasarkan laporan International Energy Agency (IEA), pada tahun 2022, pusat data di seluruh dunia mengonsumsi sekitar 460 tera watt jam listrik per tahun, yang setara dengan seluruh kebutuhan energi sebuah negara, termasuk Swedia atau Argentina. Dan angka itu terus naik, seiring dengan meningkatnya penggunaan kecerdasan buatan (AI) dan layanan aliran konten.
Bagaimana greenwashing diterapkan?
Setiap kali kita mengirim pos-el, menonton film di platform digital, atau menggunakan alat AI generatif, ada miliaran transistor di sebuah pusat data yang bekerja di balik layar. Energi untuk menjalankan semua proses itu masih bergantung pada listrik, yang sumber utamanya berasal dari bahan bakar fosil.
Google, Microsoft, dan Amazon mengklaim telah menggunakan energi terbarukan untuk sebagian operasionalnya. Namun, klaim ini sering kali berbasis pada konsep pelunasan karbon, yaitu mekanisme kompensasi emisi dengan cara membeli kredit karbon atau berinvestasi di proyek energi hijau. Dengan kata lain, bukan berarti operasi mereka bebas emisi, melainkan mereka hanya menyeimbangkan catatan di atas kertas.
Di sisi lain, ekspansi besar-besaran layanan AI pun menambah tekanan terhadap lingkungan. Model AI berskala besar memerlukan jutaan kilo watt energi untuk proses pelatihannya. Sebuah studi dari Universitas Massachusetts Amherst memperkirakan, bahwa melatih satu model bahasa besar dapat menghasilkan emisi karbon setara dengan lima mobil sepanjang masa pakainya.
Dan itu baru pada tahap pelatihan. Setelah model tersebut siap digunakan, energi yang dibutuhkan untuk menjalankan miliaran permintaan pengguna setiap harinya tentu akan menambah beban baru yang lebih besar.
Selain konsumsi energi, masalah lain yang tak kalah penting adalah limbah elektronik. Industri teknologi mempunyai kecenderungan untuk terus mendorong siklus pembaruan produk dengan cepat. Setiap tahun, produsen ponsel merilis model baru dengan sedikit perbedaan dari pendahulunya, namun dengan promosi besar-besaran tentang istilah ramah lingkungan, seperti Apple yang pada tahun 2020 memutuskan untuk tidak menyertakan pengisi daya pada paket pembelian iPhone 12, demi merawat lingkungan.
Realitasnya, banyak perangkat lama berakhir di tempat pembuangan atau dikirim ke negara-negara berkembang untuk didaur ulang secara tidak layak. Berdasarkan laporan dari Global E-Waste Monitor 2024, dunia menghasilkan lebih dari 60 juta ton limbah elektronik setiap tahun, dan hanya sekitar 20% yang benar-benar didaur ulang dengan aman.
Sebagian besar ponsel modern menggunakan logam langka seperti litium, kobalt, dan nikel yang penambangannya bisa mengakibatkan dampak sosial dan ekologis yang signifikan. Namun, alih-alih memperpanjang umur perangkat, banyak produsen malah mempersulit penggunanya untuk melakukan perbaikan sendiri, dengan alasan keamanan atau desain yang kompleks.
Posisi industri teknologi
Industri teknologi kini dihadapkan pada kenyataan yang semakin kompleks. Di satu sisi, mereka dituntut untuk terus berinovasi dan tumbuh. Di sisi lain, terdapat tanggung jawab besar terhadap dampak ekologis dari pertumbuhan itu sendiri. Banyak perusahaan berusaha menampilkan diri sebagai bagian dari solusi, tetapi sering kali hanya sampai pada tingkat narasi, bukan perubahan yang nyata.
Sebagai pengguna, kita pun tak luput dari peran dalam siklus tersebut. Kita menikmati kenyamanan layanan digital, memperbarui perangkat setiap beberapa tahun, dan memindahkan sebagian kehidupan kita ke data digital, tanpa banyak memikirkan energi yang dibutuhkan untuk menopang semua itu.
Dalam situasi seperti inilah greenwashing tumbuh subur. Janji ramah lingkungan menjadi bahasa pemasaran yang mudah diterima publik, terutama ketika rasa bersalah terhadap krisis iklim mulai bermunculan. Banyak perusahaan berbicara tentang efisiensi dan netralitas karbon, namun hanya sedikit yang membuka data tentang konsumsi energi, daur ulang, atau umur produk mereka.
Keberlanjutan bukan soal menebus emisi dengan kredit karbon, melainkan mengubah cara berpikir tentang pertumbuhan itu sendiri. Tidak semua kemajuan berarti produksi yang lebih banyak, atau konsumsi lebih cepat. Kadang, langkah yang paling tepat untuk dilakukan ialah berhenti sejenak dan bertanya, apakah teknologi yang kita ciptakan dan gunakan benar-benar dibutuhkan?
Mungkin itulah ukuran moral yang tepat bagi industri teknologi saat ini. Bukan seberapa cepat mereka berinovasi, tetapi seberapa jujur mereka menilai dampak dari inovasi itu sendiri.
Kemajuan yang kita butuhkan
Kita hidup di masa ketika ramah lingkungan menjadi kata kunci dalam strategi komunikasi korporasi. Namun mungkin inilah saatnya untuk membedakan antara hijau yang nyata dan hijau yang sekadar kosmetik.
Teknologi seharusnya membantu manusia untuk hidup lebih baik, bukan sekadar lebih cepat, lebih efisien, atau lebih canggih, tetapi lebih bijak terhadap bumi yang menanggung akibatnya.
Greenwashing dalam industri teknologi bukan hanya tentang pencitraan palsu. Ia mencerminkan dilema moral tentang bagaimana kemajuan didefinisikan. Ketika kemajuan selalu diukur dari pertumbuhan dan konsumsi, maka warna hijau hanya akan muncul di layar monitor kita, bukan dari bumi yang sedang berbahagia. Dan itu bukan kemajuan yang kita butuhkan.