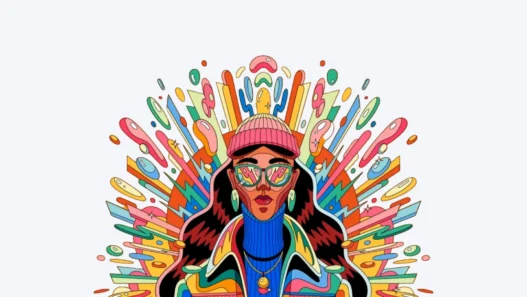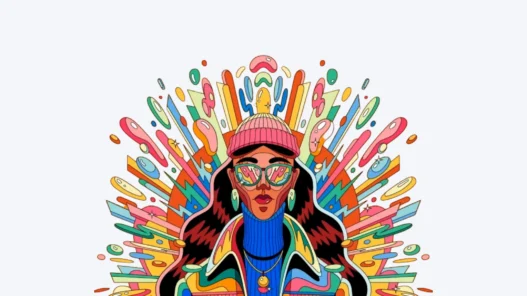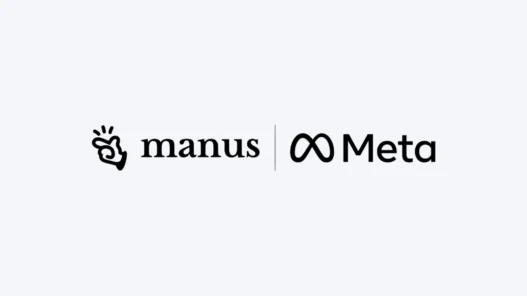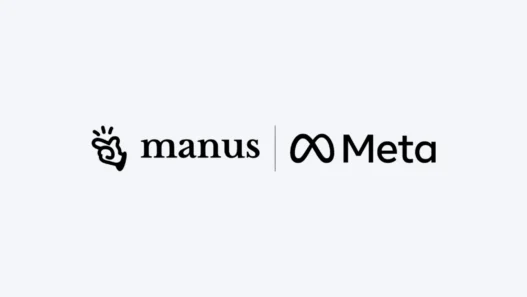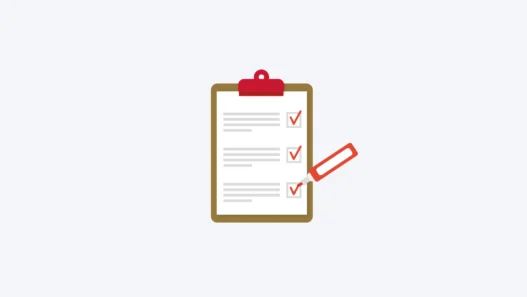Marilah kita mencoba untuk jujur sejenak. Kapan terakhir kali kita benar-benar berpikir keras sebelum mencari jawaban di internet? Mungkin sudah lama sekali. Sekarang, bahkan untuk pertanyaan sederhana sekalipun, dari resep masakan hingga argumen filsafat, semua bisa dicari dalam hitungan detik.
Di ruang kelas, di kantor, bahkan di rumah, kita hidup dalam ekosistem yang menyanjung efisiensi. Kita menyukai segala sesuatu yang cepat, rapi, dan instan. Maka, ketika kecerdasan buatan (AI) hadir menawarkan jalan pintas baru, dalam menulis esai, menyusun laporan, dan bahkan membuat keputusan, kita menyambutnya dengan sukacita.
Tetapi di balik kemudahan itu, ada sesuatu yang diam-diam tergerus: daya tahan kita terhadap kesulitan berpikir. Bukan AI yang mengakibatkan hal itu terjadi. Kitalah yang menyediakan panggungnya; yang mana para pendidik, orang tua, dan masyarakat sudah terlalu lama menganggap hasil sebagai bukti suatu kecerdasan, bukan sebuah proses.
AI dan hilangnya dorongan mental
AI, pada dasarnya, adalah mesin yang menghapus dorongan: dorongan dalam berpikir, menulis, atau mengambil keputusan. Ketika dulu siswa perlu berjam-jam merangkai kata untuk menulis esai, kini mereka hanya perlu satu kalimat perintah, seperti “tulis esai tentang perubahan iklim.” Dalam beberapa detik, esai terbuat, dengan hasil yang rapi, logis, dan nyaris sempurna.
Di situlah masalahnya. Dalam setiap dorongan — kebuntuan, frustrasi, atau kesalahan — sejatinya terdapat proses pembentukan intelektual. Pikiran manusia tumbuh bukan ketika jawaban ditemukan, tetapi ketika kita berjuang untuk mencarinya. Seperti otot, kecerdasan pun butuh beban. Ketika semua dorongan dihapus oleh alat bantu digital, proses pembentukan itu ikut lenyap.
AI tidak merusak kemampuan kita berpikir. Ia hanya mengeksploitasi kelemahan budaya kita: ketidaksabaran terhadap proses yang lambat dan tidak pasti.
Budaya cepat, hasil cepat, salah siapa?
Kini kita hidup di tengah generasi yang tumbuh dengan logika hasil instan. Sistem pendidikan kita menilai angka, bukanlah argumen. Orang tua memuji nilai seratus, bukan upaya yang panjang di balik angka itu. Perusahaan memberi bonus untuk target yang telah tercapai, bukan untuk ide-ide yang belum selesai meskipun menjanjikan.
Ketika AI masuk di kehidupan kita, ia hanya memperkuat sistem yang sudah ada. Di berbagai universitas dunia, fenomena ini sudah terlihat. Sebuah survei di Inggris menemukan bahwa ribuan mahasiswa kedapatan menggunakan AI untuk menulis tugas akademik yang diberikan.
Di Indonesia, fenomena penggunaan AI di lingkungan pendidikan diterima secara sosial. Menurut beberapa survei, lebih dari 86 persen pelajar di Indonesia mengaku menggunakan AI untuk mengerjakan tugas sekolah atau kuliah, dan sebagian guru bahkan mendorong praktik tersebut dengan alasan mengikuti perkembangan zaman.
Hal itu bukan kesalahan AI. Ia hanya cerminan dari bagaimana kita mendidik dan menilai. Kita telah membangun masyarakat yang tidak memberi ruang untuk berbuat salah, padahal kesalahan adalah bahan bakar utama untuk belajar dan menjadi lebih baik dari sebelumnya.
Hal serupa terjadi di dunia kerja. Banyak perusahaan kini menilai karyawan berdasarkan produktivitas kuantitatif, yakni berapa cepat laporan selesai, berapa banyak ide yang dihasilkan, tanpa mempertimbangkan kedalaman berpikir di balik semua itu.
Maka, saat AI menawarkan efisiensi di kehidupan kita, siapa yang bisa menolak? Ironinya, kita tidak sadar bahwa kita sedang menghapus kebutuhan akan kemampuan yang paling manusiawi, yaitu kemampuan untuk berpikir kritis dan bertahan dalam ketidaktahuan.
Kita, sang arsitek ilmu pengetahuan
Menyalahkan generasi muda karena mereka malas berpikir sama dengan menyalahkan ikan yang tidak bisa terbang. Mereka tumbuh di kolam yang kita isi sendiri, yaitu kolam yang dangkal, nyaman, dan berarus cepat.
Sebagai pendidik, kita kerap lebih bangga pada siswa yang menyelesaikan tugas dengan cepat daripada siswa yang berani bertanya. Sebagai orang tua, kita kerap lebih tenang ketika melihat anak sedang fokus belajar, daripada sedang menatap langit sambil berpikir lama. Sebagai masyarakat, kita lebih mudah membuat viral kesuksesan yang instan, daripada proses panjang untuk menggapai kesuksesan itu, yang dipenuhi beribu kegagalan.
AI hanyalah akselerator dari budaya yang sudah rapuh. Ia mempercepat apa yang sudah kita biasakan, yakni ketergantungan pada hasil, serta alergi terhadap proses. Kita membesarkan generasi yang tahu cara memperoleh jawaban, namun tidak tahu cara mencari kebenaran atas jawaban tersebut.
Meski demikian, malas berpikir bukanlah suatu kebodohan, melainkan gejala dari ketidaksabaran. Kita kerap tidak membiasakan otak kita mengalami masa frustrasi produktif, momen ketika kebuntuan dapat melatih ketahanan kognitif. Dalam istilah psikologi pendidikan, inilah yang disebut desirable difficulty, yakni kesulitan yang dibutuhkan agar kita dapat benar-benar belajar.
Saat semua kesulitan dihapus oleh alat bantu seperti AI, kita kehilangan peluang untuk mengasah otot mental itu. Kita menjadi rapuh secara intelektual. Kita mudah kagum, mudah menyerah, dan mudah percaya pada hasil yang tampak meyakinkan meski tidak mempunyai nilai kebenaran.
Mengembalikan nilai perjuangan
Kita tidak dapat dan tidak perlu menyingkirkan AI dari kehidupan. Yang dapat kita ubah adalah bagaimana kita memaknai berpikir. Mungkin sudah saatnya kita berhenti menganggap kebuntuan sebagai kegagalan. Justru dari sanalah kita belajar. Saat siswa berdebat dengan dirinya sendiri, ketika penulis macet di tengah paragraf, atau ketika pekerja bingung mencari solusi — itu bukan tanda kelemahan, melainkan bukti bahwa otak kita sedang bekerja.
AI bisa menulis lebih cepat, menjawab lebih tepat, dan memprediksi lebih akurat. Tetapi ia tidak bisa merasa bingung. Dan kebingungan, dalam takaran tepat, adalah sumber kreativitas manusia.
Jadi pertanyaannya bukan apakah AI membuat kita malas berpikir, tetapi apakah kita masih berani memberi ruang bagi kesulitan dan kegagalan? Karena tanpa kesulitan, tidak ada kedalaman. Tanpa kegagalan, tidak ada kebijaksanaan. Dan apabila kita menghapus keduanya demi efisiensi, kita bukan sedang membentuk masa depan yang cerdas — kita sedang mencetak generasi yang rapuh.